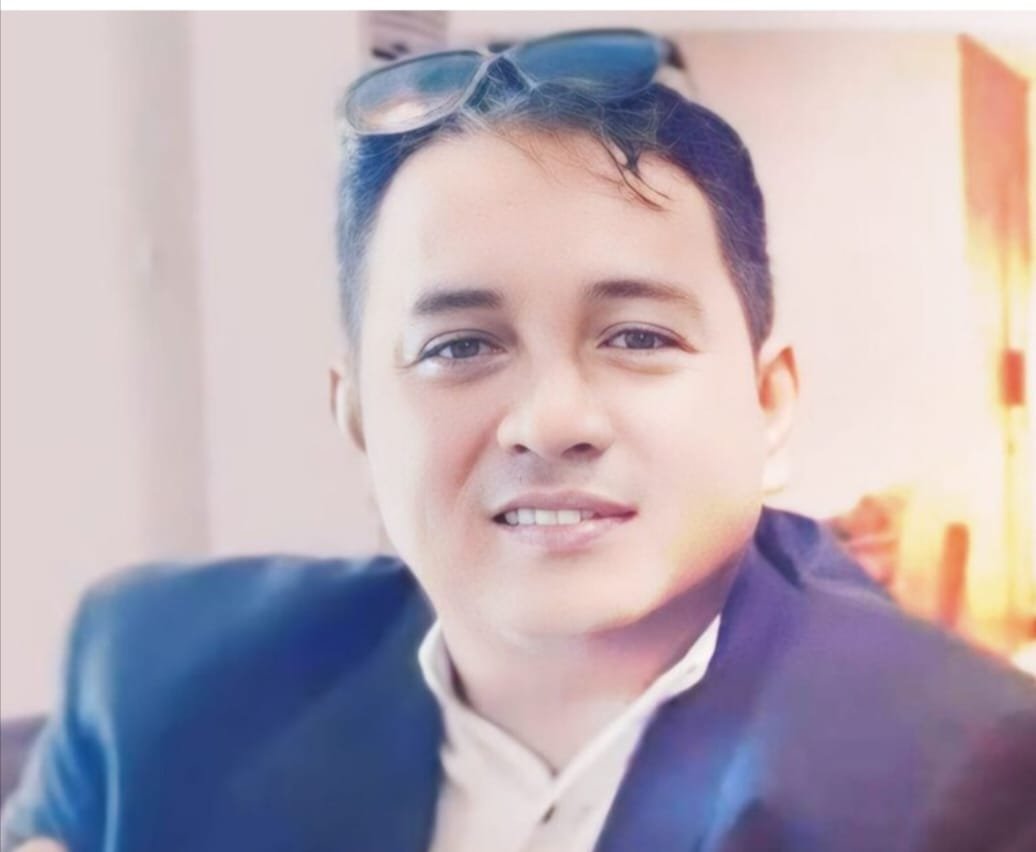KBOBABEL.COM – Sudah saatnya kita mengajukan pertanyaan yang paling jujur dan paling mendasar:
Masihkah rakyat menjadi pemilik sejati atas kekayaan alam negeri ini?
Pertanyaan ini bukan lahir dari sikap pesimis, apalagi dari kebencian. Ia lahir dari kesadaran, dari keprihatinan yang tumbuh di dalam dada banyak anak bangsa—bahwa semakin hari, jarak antara rakyat sebagai pemilik tanah dan mereka yang mengelola atas nama negara, justru semakin melebar.
Seolah tanah ini hanya boleh disentuh oleh mereka yang berkantong tebal, berlabel resmi, dan punya kedekatan dengan kekuasaan.
Sementara rakyat yang sejak lama hidup dan menggantungkan hidup dari tanahnya sendiri, justru menjadi tersangka di kampungnya sendiri.
Saya lahir dan tumbuh besar di Pulau Bangka.
Di sini, timah bukan sekadar bahan tambang—ia adalah denyut nadi kehidupan.
Namun sebelum kata “tambang” akrab di telinga, kami sudah lebih dulu akrab dengan tanah, air, dan hasil buminya.
Kami bukan pendatang di atas tanah ini. Kami bukan pengganggu. Kami adalah bagian darinya.
Rakyat adalah pemilik daulat wilayah ini, jauh sebelum negara mencatatnya sebagai aset, dan jauh sebelum perusahaan diberi mandat untuk mengelola.
Negara hadir untuk mengatur, bukan menggusur.
Perusahaan hadir untuk membantu mengelola, bukan mengambil alih.
Namun dalam praktiknya, apa yang terjadi hari ini seolah membalikkan logika itu.
Rakyat hanya menjadi angka statistik.
Pemilik sah menjadi tamu di rumahnya sendiri.
Dalam perumpamaan sederhana:
Rakyat adalah pemilik proyek. Negara adalah arsitek perencana. Perusahaan tambang adalah kontraktor pelaksana.
Tapi entah sejak kapan, kontraktor mulai bertingkah seperti pemilik.
Ia menyusun aturannya sendiri, menyeleksi siapa yang boleh hidup dari tanah ini, dan siapa yang akan dianggap pengganggu.
Bahkan lebih ironis, pemilik tanah kini harus meminta restu dari kontraktor—lengkap dengan segala syarat administrasi dan regulasi yang entah disusun untuk siapa.
Yang jelas, bukan untuk rakyat kecil.
Dan lebih menyakitkan lagi, ketika kontraktor itu justru menyelewengkan amanah sebesar Rp271 triliun, tidak hanya merobek kepercayaan rakyat, tapi juga mempermalukan negara di depan sejarahnya sendiri.
Satu skandal yang membuat kita bertanya:
Siapa sebenarnya yang harus diadili dalam sistem ini?
Rakyat yang menambang untuk makan, atau kontraktor yang menggerogoti miliaran dari mandat rakyat?
Kami, para anak negeri, bukan ingin menentang mandat negara.
Kami hanya ingin diingatkan kembali:
bahwa tanah ini milik rakyat, dan tidak sepatutnya rakyat merasa asing di tanahnya sendiri.
Kami tahu, saat ini hanya PT Timah yang mendapat kewenangan resmi dari negara untuk mengelola pertambangan timah.
Kita tahu mandat itu bukan main-main. Tapi kami juga tahu, mandat tanpa kepercayaan rakyat hanya akan menjadi legitimasi kosong.
Maka walaupun hati ini masih menyimpan luka, dan kepercayaan itu telah retak,
kami tetap datang, bukan sebagai pesaing, bukan pula pengacau.
Kami datang karena tak punya pilihan lain, kecuali bermitra dengan satu-satunya institusi yang ditunjuk negara sebagai operator.
Sekalipun kami merasa dizalimi,
rakyat masih percaya bahwa jalan perubahan bisa lahir dari dialog dan keterbukaan.
Pelajaran dari Sejarah
Mari kita buka kembali lembaran sejarah bangsa ini.
Reformasi 1998 tidak lahir dari restu kekuasaan.
Ia lahir dari keberanian rakyat untuk berubah, ketika ruang demokrasi dikunci dan suara rakyat dikecilkan.
Sejarah selalu punya satu hukum abadi:
Jika ruang aspirasi terus ditutup, maka tekanan akan mencari jalan keluar.
Dan ketika titik nadir kesabaran itu tiba, perubahan bukan lagi sekadar tuntutan—tapi keniscayaan.
Rakyat bisa diam,
bisa bertahan,
bisa menahan rasa kecewa.
Tapi bukan berarti mereka rela kehilangan haknya.
Bila suara rakyat terus diabaikan, maka arus perubahan akan datang, entah disambut atau ditolak.
Penutup
Kini, izinkan saya bertanya satu hal, bukan kepada penguasa, bukan kepada pengusaha—tetapi kepada nurani kita bersama:
Apakah masih ada ruang bagi rakyat dalam pengelolaan kekayaan alamnya sendiri?
Ataukah kita terus membiarkan pemilik sejati menjadi penonton,
sementara yang diberi mandat bertindak seolah dialah empunya negeri?
Jika benar negara ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,
maka sudah semestinya suara rakyat kembali menjadi kompas arah kebijakan.
Bukan untuk menguasai,
tetapi untuk menjaga dan merawat haknya sebagai pemilik yang sah atas tanah, air, dan masa depan bangsa ini.
Tentang Penulis:
Muhamad Zen adalah seorang jurnalis dan aktivis masyarakat sipil asal Kepulauan Bangka Belitung. Zen dikenal sebagai sosok yang konsisten mengawal demokrasi, keterbukaan informasi publik, dan penguatan peran masyarakat sipil di daerahnya.
Selain sebagai wartawan, Zen juga dikenal luas sebagai penggerak berbagai organisasi masyarakat. Ia aktif membangun jejaring dengan ormas, organisasi kepemudaan (OKP), LSM, serta komunitas lokal guna memperkuat daya tawar masyarakat di hadapan pemangku kepentingan. Prinsipnya sederhana namun kuat: masyarakat harus mendapat tempat yang adil dalam kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam.
Tulisan ini adalah suara pribadi yang lahir dari nurani warga yang mencintai tanahnya. Jika ada pihak yang merasa tersentil, semoga itu menjadi jalan untuk membuka mata dan hati, Karena tujuan tulisan ini bukan menyalahkan, tapi mengajak pulang: kepada keadilan, kepada keberpihakan, dan kepada kedaulatan rakyat itu sendiri.
———————–
Catatan Redaksi:
Isi narasi opini ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas penyajian artikel ini, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita sanggahan/koreksi kepada redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sanggahan dapat dikirimkan melalui email atau nomor WhatsApp redaksi sebagaimana tertera pada box Redaksi.